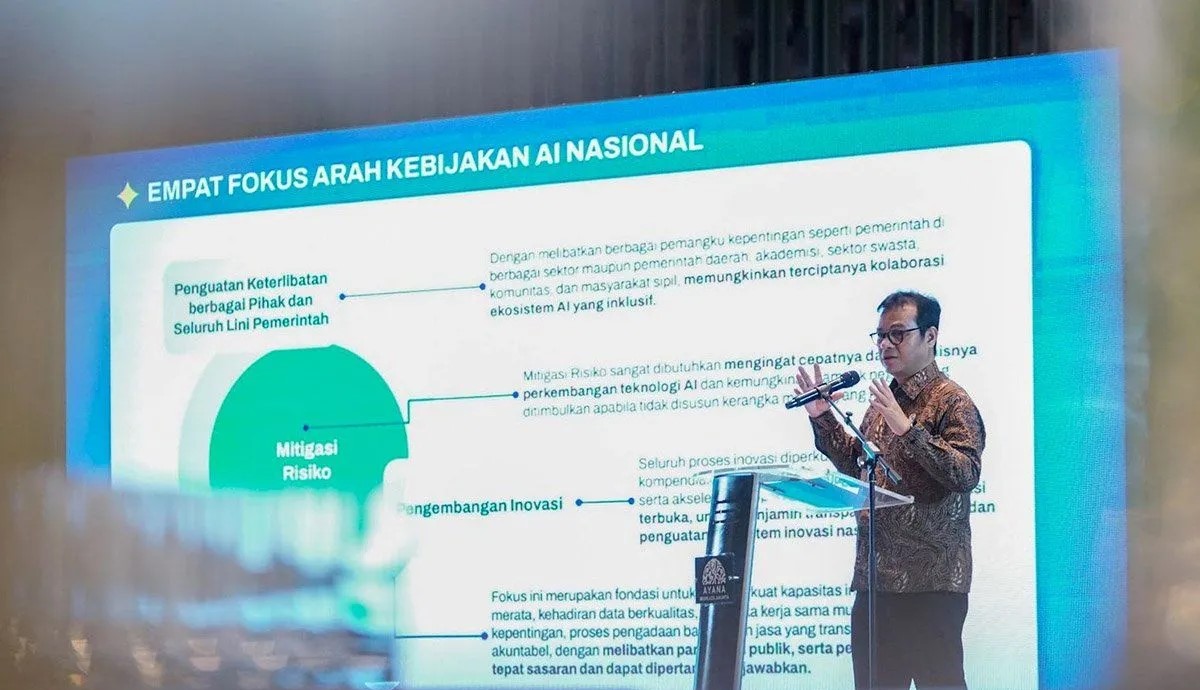Sekilas.co – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital tengah menelaah secara serius usulan regulasi yang diajukan oleh Komisi I DPR terkait pembatasan kepemilikan akun media sosial, yakni satu orang hanya diperbolehkan memiliki satu akun. Wacana ini muncul sebagai jawaban atas keresahan publik yang semakin meluas mengenai derasnya arus hoaks, ujaran kebencian, hingga praktik manipulasi opini yang sering kali dilakukan oleh akun anonim maupun jaringan buzzer.
Menurut salah seorang anggota Komisi I DPR, penerapan identitas tunggal di ruang digital diyakini dapat menumbuhkan tanggung jawab pribadi setiap pengguna dalam bermedia sosial. Dengan kewajiban menggunakan identitas asli, diharapkan masyarakat tidak mudah menyalahgunakan kebebasan berekspresi untuk merugikan orang lain atau menyebarkan konten berbahaya.
Namun demikian, gagasan ini masih menuai perdebatan. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah: benarkah satu akun per orang dapat menjadi solusi jitu? Sejumlah pengalaman negara lain justru menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar pembatasan jumlah akun.
Korea Selatan, misalnya, pernah memberlakukan aturan penggunaan nama asli di internet pada tahun 2007. Alih-alih efektif, kebijakan itu hanya mampu menekan komentar jahat kurang dari satu persen, sementara mayoritas pengguna justru beralih ke platform luar negeri yang tidak memberlakukan aturan serupa. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi Korea pada 2012 memutuskan aturan tersebut tidak konstitusional karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
China menempuh jalur berbeda melalui sistem real-name registration yang terpusat. Seluruh pengguna internet diwajibkan menghubungkan akun digital dengan identitas resmi yang dikelola pemerintah. Sistem ini memang disebut-sebut berhasil meningkatkan kepercayaan publik di ruang digital, tetapi sekaligus menuai kritik keras. Para pengamat menilai, kebijakan tersebut membuka jalan bagi praktik pengawasan massal yang mengancam privasi dan memperbesar kendali negara terhadap warganya. Identitas tunggal memang dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi dengan harga yang mahal: hilangnya privasi dan terbatasnya kebebasan individu.
Suara dari para pemikir juga patut diperhatikan. Filsuf Michel Foucault lewat konsep panopticon mengingatkan bahwa masyarakat yang selalu merasa diawasi lambat laun akan kehilangan kebebasan berekspresinya. Zygmunt Bauman, seorang sosiolog ternama, menekankan bahwa identitas manusia di era modernitas cair bersifat fleksibel dan terus berubah. Dengan demikian, pemaksaan terhadap satu identitas tunggal justru bertentangan dengan realitas sosial kontemporer. Dunia digital pada hakikatnya memberikan ruang bagi identitas cair, seseorang bisa tampil sebagai profesional, aktivis, sekaligus pribadi dalam konteks yang berbeda-beda.
Sementara itu, Hannah Arendt mengingatkan pentingnya ruang publik sebagai arena pluralitas. Justru karena adanya kesempatan berbicara secara anonim, kelompok lemah dapat memiliki suara. Dalam konteks tertentu, anonimitas adalah perisai demokrasi. Shoshana Zuboff melalui konsep surveillance capitalism menambahkan dimensi lain: data pribadi bisa dieksploitasi korporasi untuk keuntungan ekonomi. Artinya, kebijakan satu akun per orang berpotensi memperbesar risiko komersialisasi data warga.
Situasi di Indonesia menambah kerumitan. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan pada 2022, implementasinya masih jauh dari harapan. Sejumlah kebocoran data besar pernah terjadi, mulai dari 279 juta data BPJS Kesehatan yang dijual di forum daring, kebocoran daftar pemilih tetap Pemilu 2024, hingga peretasan data e-commerce besar yang merugikan jutaan pengguna. Semua ini mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan negara maupun platform digital dalam menjaga keamanan data pribadi. Bagaimana mungkin masyarakat percaya pada kebijakan identitas tunggal jika data resmi mereka saja kerap bocor dan diperdagangkan secara bebas?
Alih-alih meningkatkan akuntabilitas, penerapan satu akun per orang justru berpotensi menambah risiko. Konsentrasi data pribadi dalam satu sistem membuatnya menjadi sasaran empuk bagi peretas, sekaligus rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki akses sah namun tidak bertanggung jawab. Tanpa fondasi keamanan digital yang kokoh, kebijakan semacam ini ibarat membangun rumah megah di atas pasir yang rapuh.
Jalan tengah sebenarnya tetap terbuka. Persoalan bukanlah jumlah akun, melainkan akuntabilitas. Seseorang tetap bisa memiliki lebih dari satu akun asalkan seluruhnya terverifikasi. Verifikasi tidak harus berarti menyingkap identitas ke publik; cukup agar dapat dilacak ketika ada pelanggaran hukum. Dengan cara ini, privasi tetap terlindungi, tetapi penegakan hukum juga bisa berjalan.
Sistem verifikasi berlapis bisa menjadi solusi: akun biasa cukup dengan nomor ponsel, sementara akun yang ingin menyiarkan iklan politik, mengelola komunitas besar, atau menjadi penyebar konten berpengaruh wajib menggunakan identitas resmi. Dengan begitu, ruang berekspresi tetap luas, tetapi pihak-pihak dengan pengaruh signifikan lebih mudah dimintai pertanggungjawaban.
Selain itu, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemerintah. Platform digital global seperti Meta, X, dan TikTok harus ikut serta dalam moderasi konten dengan cara transparan dan akuntabel. Literasi digital juga menjadi benteng utama: masyarakat yang kritis akan lebih tahan terhadap hoaks dan manipulasi. Program literasi harus menjangkau sekolah, kampus, hingga komunitas lokal.
Perlindungan khusus bagi kelompok rentan tidak boleh diabaikan. Aktivis HAM, jurnalis investigatif, kelompok minoritas, hingga korban kekerasan sering kali bergantung pada anonimitas untuk keselamatan mereka. Jika kebijakan dipukul rata, ruang kritik bisa terhenti. Seperti diingatkan Arendt, pluralitas adalah inti kebebasan politik, dan anonimitas kadang merupakan syarat bagi pluralitas itu sendiri.
Dengan demikian, kebijakan ideal harus bisa membedakan antara anonimitas yang melindungi suara lemah dan anonimitas yang digunakan untuk menyebar kebencian atau manipulasi publik. Ruang digital yang sehat lahir dari keseimbangan antara kebebasan dan keamanan, bukan dari kontrol yang berlebihan.
Kebijakan satu akun per orang terdengar sederhana, tetapi risiko yang menyertainya tidak kecil, mulai dari represi, kebocoran data, hingga hilangnya keberanian untuk bersuara. Seperti kata Bauman, identitas manusia bersifat cair. Yang dibutuhkan bukanlah identitas yang dipaksakan, melainkan identitas digital yang dapat dipercaya. Ruang digital adalah cermin dari demokrasi kita: bila diisi rasa takut, demokrasi akan kehilangan ruhnya; tetapi bila diisi rasa percaya, kebebasan dan akuntabilitas justru dapat tumbuh berdampingan.